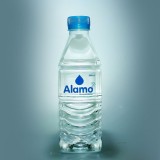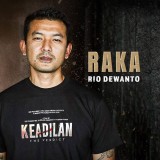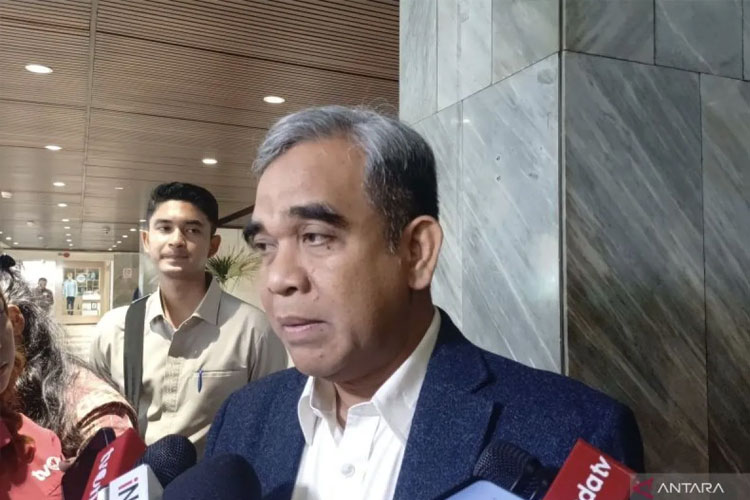TIMES SEMARANG, SEMARANG – Lanskap sosial-keagamaan masyarakat Indonesia diwarnai oleh pemandangan yang terus saja berulang, seperti antrean panjang warga untuk mendapatan zakat (mal atau fitrah).
Tidak hanya itu, spanduk lembaga atau badan amil zakat yang bertebaran, dan memberikan pesan-pesan tentang kewajiban membersihkan harta. Semua merupakan praktik mulia yang sudah mengakar kuat.
Namun, di tengah ritual tahunan tersebut, masih saja sering kali kita lepas dari pertanyaan yang fundamental. Mengapa tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial di negara tercinta ini dan mempunyai potensi zakat yang besar masih begitu sangat mengkhawatirkan?
Hipotesisnya bisa jadi karena beda cara melihatnya, bagaimana kita melihat pada zakat itu. Yang sudah berjalan, zakat masih direduksi menjadi sekadar amal personal, yang hanya untuk mencukupi kebutuhan transaksi vertical langsung kepada Allah dan bermanifestasi horizontal pada pemberian karitas.
Padahal, jika kita bisa mengulik lebih jauh dan mendalam pada tujuan-tujuan hukum Islam (Maqashid Syariah) zakat dapat dirancang sebagai salah satu tujuan yang lebih besar, yaitu sebuah instrumen kebijakan fiskal Illahi yang tersistem dan bertujuan untuk merestrukturisasi sistem ekonomi dan menegakkan keadilan sosial. Karena sudah saatnya kita harus merubah paradigma, dari melihat zakat sebagai ritual amalan pribadi menjadi pilar keadilan ekonomi yang strategis.
Tantangan terbesar dalam pengelolaan praktik zakat kontemporer adalah efektivitas penyaluran. Niat baik dari para pembayar zakat (muzakki) dan kerja keras dan tanggungjawab para pengelola zakat (amil) tentu sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun, metode penyaluran yang dominan masih bersifat konsumtif dan hanya untuk kebutuhan jangka pendek.
Santunan tunai anak yatim, pembagian sembako, atau dalam bentuk bingkisan lebaran memang memberikan Kesan dan kelegaan sesaat bagi para penerima zakat (mustahik), tapi ternyata masih gagal memutus rantai kemiskinan yang membelenggu masyarakat.
Praktik pemberian zakat yang dilakukan dengan cara yang bersifat konsumtif bisa diibaratkan hanya memberikan ikan, tapi tidak memberikan kail. Sehingga, ketika ikan yang diberikan habis, tentu saja penerima akan mencari lagi untuk mendapatkan ikan itu.
Dan akan terus berulang setiap ikan itu habis, dan menunggu atau mencari agar ada yang memberikannya lagi. Karena ketika sifat zakat masih berkonsep konsumtif, hanya akan bisa menolong orang yang lapar pada hari itu, tetapi tidak akan bisa menjamin apakah besok akan bisa makan lagi atau tidak.
Konsep zakat supaya bisa benar-benar menjadi instrumen keadilan, penyalurannya harus berorientasi pada program produktif. Bayangkan jika dana zakat yang masif dialokasikan secara terukur dan terencana untuk modal usaha ultra-mikro, beasiswa pendidikan kejuruan yang relevan dengan pasar kerja, pelatihan keterampilan atau bantuan alat-alat produksi.
Model seperti ini yang akan bisa mengubah status mustahik menjadi muzakki diwaktu yang akan datang. Beberapa lembaga atau badan zakat sudah mulai ada yang bergerak mengarah ke ke arah tersebut, namun skalanya sepertinya masih perlu diperbesar dan pengawasan dan evaluasi perlu diperkuat, supaya tidak berhenti ditengah jalan.
Menggali Potensi yang Redup
Diskursus terkait zakat di masyarakat sering kali masih terpaku pada zakat mal yang bersifat tradisionalis seperti emas, perak, dan hasil pertanian. Padahal, kantong-kantong kekayaan dalam ekonomi saat ini sudah mulai bergeser. Dua potensi raksasa yang belum terpegang secara optimal adalah zakat profesi dan zakat korporasi.
Para profesional dengan pendapatan tinggi seperti hakim, dokter, pengacara, konsultan, anggota dewan, eksekutif dan lainnya tentu saja mempunyai potensi zakat yang besar. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki laba miliaran hingga triliunan rupiah per tahunnya. Jika potensi zakat tersebut mampu dihimpun secara sistematis, jumlahnya tentu akan mampu melampaui pengumpulan zakat saat ini.
Metode tersebut tentunya membutuhkan regulasi yang sangat jelas, fatwa yang progresif dari ulama, serta kesadaran kolektif dari para pelaku usaha dan profesional untuk menunaikan kewajibannya, bukan sekadar sebagai tanggung jawab sosial saja, melainkan sebagai kewajiban spiritual yang bisa berdampak struktural.
Proses yang berjalan saat ini, antara lembaga atau badan zakat dan pemerintah seolah berjalan di relnya masing-masing, yang tentu jarang sekali bersinggungan. Pemerintah tentu mempunyai program untuk mengentaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, dengan anggaran dan data yang komprehensif.
Dilain sisi, lembaga atau badan zakat mempunyai gerakan yang lincah, jaringan yang kuat di akar rumput dan sentuhan spiritual yang tidak ada pada birokrasi pemerintahan.
Sebagai pengganti berkompetisi atau berjalan masing-masing, sinergi bersama merupakan sebuah kunci yang harus dilakukan. Bayangkan saja dengan model skema di atas, Dimana pemerintah sebagai penyedia data yang akurat (by name dan by address) terkait dengan lokasi-lokasi kemiskinan yang sangat ekstrem.
Kemudian lembaga atau badan zakat berjalan dengan dana zakat untuk melakukan intervensi yang lebih spesifik dan terarah, misalnya adalah program pemberdayaan ekonomi atau pendampingan usaha pada masyarakat, yang tentunya itu belum mampu tercover dengan skema bantuan dari pemerintah.
Dengan kolaborasi tersebut, nantinya pasti akan tercipta ekosistem pengentasan kemiskinan yang holistik. Dimana dana negara dan dana umat bisa saling berkolaborasi melengkapi terciptanya dampak baik dari hasil kolaborasi keduanya yang lebih baik.
Zakat dipandang tidak hanya sebagai amal tahunan yang bisa dilihat sebagai penyia-nyiaan terhadap potensinya yang lebih baik. Tetapi zakat adalah cetak biru Illahi untuk keadilan distributif, sebuah sistem jaring pengaman sosial yang dirancang untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Karena zakat sejatinya adalah bukan sekadar tentang bagaiamana cara membersihkan harta, melainkan tentang membersihkan masyarakat dari penyakit ketimpangan sosial.
***
*) Oleh : Abdus Salam, Pengajar di FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta dan Staf Yayasan ELSA Semarang.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |